Aku Manusia?
(Gubahan: Me Midad Ei Ak)
“Mengertilah, kau bukanlah Malaikat yang selalu bersujud kepada-Nya, dan kau bukanlah Syaitan yang selalu membangkang dari-Nya. Kau adalah manusia. Mengertilah manusia, Tio.”
“Tio, kau mau kemana? Rapat belum selesai nih!” Abil, yang sedang memimpin rapat asrama, bersorak tegas memanggilku tatkala kugapai sepasang sandal dari rak. Aku pun menoleh ke belakang. Semua bola mata yang ada di selasar asrama tertuju padaku.
“Ke masjid lah dil, kalian gag dengar adzan? Panggilan Allah tuh.” Aku pun bergegas menuju masjid, tak jauh dari asrama.
***
Perkenalkanlah, aku Tio. Seorang remaja yang mulai beranjak dewasa, terlahir di Kota Melayu Deli. Tahukah kalian kota manakah itu? Kota Melayu Deli adalah sebuah julukan dari Kota Medan. Julukan kotaku tersebut diambil dari nama Kesultanan Melayu yang didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah pada tahun 1632, yakni Kesultanan Deli. Hingga saat ini, Kesultanan Deli masih tetap ada walaupun tidak lagi mempunyai kekuatan politik yang kuat semenjak perang dunia II dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.
Aku tinggal bersama kedua orang tuaku di daerah yang cukup primitif. Listrik hanya hidup 4 jam di malam hari yang dibantu dengan tenaga diesel. Dulu, waktu aku masih di sekolah dasar, aku harus berjalan menembus hutan selama lebih dari satu jam perjalanan menuju sekolahku. Dan untuk makan sehari-hari, aku pun harus berburu, mencari hewan yang berkeliaran.
Kini, aku telah beranjak dewasa. Aku telah lulus dari salah satu pondok terkenal yang ada di kota dengan predikat sebagai lulusan terbaik. Siapa yang tak mengenaliku, disamping lulusan terbaik, aku juga menyandang sebagai siswa teladan pada saat itu. Bahkan, anak putri yang ada di belakang dinding tinggi sana, juga mengetahuiku. Entah bagaimana caranya nama yang sesederhana ini bisa sampai pada mereka. Yang jelas, nama Tio tak asing lagi tuk didengar.
***
“Ctaaak, ctaaak …” suara sandal yang kulemparkan dan kemudian kupakai. Shalat maghrib selalu menjadi hal yang menjadikan hatiku tenang. Aku pun berjalan santai menuju kamar. Ku lihat teman-temanku baru saja menyelesaikan rapatnya. Mereka beranjak berdiri.
“Gimana hasil keputusan rapatnya?” aku bertanya dengan sangat antusias. Mereka saling bertatapan satu dengan yang lain.
“Hey, aku tanya ini, kok gag ada yang jawab?” sekali lagi kutegaskan agar mereka mau menjawabnya. Namun, mereka tetap saja diam dan melirik satu dengan yang lain. Hingga salah satu dari mereka berceloteh.
“Hasilnya, kau bukan lah manusia, Tio. Kau memang seperti Malaikat!”
Tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Aku tak mengerti, mengapa mereka tertawa? Apanya yang lucu? Perasaan gag ada yang lucu, gumamku dalam hati. Bukan kah malaikat itu lebih baik dari manusia, karena ia tak pernah berdusta kepada-Nya. Aku pun tersenyum datar melihat tingkah mereka yang aneh itu, menganggap mereka hanya sebatas bercanda. Tak ada yang perlu difikirkan. Dan semua kejadian aneh itu hilang bersamaan dengan silir angin malam.
Sudah hampir satu tahun aku meninggalkan Kota Melayu Deli. Tepatnya di Kota Pelajar aku akan tinggal selama tiga sampai empat tahun ke depan. Benar sekali, Kota Yogyakarta. Aku meneruskan jenjang kuliah di salah satu Universitas Islam di Kota Pelajar ini. Kesan pertama yang kurasakan ketika menginjakkan kaki di bumi Jawa, semua orang disini sopan-sopan. Sebuah kesimpulan yang entah benar ataupun tidak. Kulihat mereka tak segan tuk menyapa satu sama lain tatkala berpapasan. Monggo adalah kata yang sering kudengar, yang dulu aku tak tau apa artinya.
Ngomong-ngomong kejadian semalam, kejadian aneh itu bukanlah yang pertama bagiku. Sebelum-sebelumnya, mereka juga pernah bertingakah aneh di hadapanku. tepatnya, ketika salah satu dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerengakan suatu materi. Aku pun dengan gesit mengacungkan tangan, Secepat-cepatnya. Tak mau ada seseorang pun mendahuluiku. Hasilnya, selalu aku lah yang lebih dahulu. Dan sampai saat ini, belum pernah ada seorang pun yang dapat mendahuluiku. Tak kan kubiarkan itu terjadi. Aku bangga dengan semua ini.
Setelah dosen mempersilahkanku untuk menerangkan materi, aku pun maju dengan segagah mungkin. Layaknya ku telah menguasai penuh materi yang akan kujelaskan. Sedikit membenahkan kerah baju, kemudian dengan perlahan ku melangkahkan kaku, menggapai spidol yang tergeletak di meja dosen.
Kali ini, tak seperti biasanya, aku tegang berada di hadapan teman-teman. Tak satu pun dari mereka memperhatikanku. Sebagian dari mereka melirik satu dengan yang lain—tingkah yang sama dengan kejadian kemarin sore, dan sebagian yang lain sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang membaca buku, menulis sesuatu di buku tulis bahkan diam-diam main gadget.
Tingkah aneh mereka membuatku semakin tegang dan merasa dilecehkan. Tubuhku pun bermandikan peluh, padahal ruangan ini ber-AC. Ada apa dengan mereka?, mengapa mereka tidak memperhatikanku?, ada yang salah kah dengan penampilanku?, pertanyaan yang hanya bisa kukatakan dalam benak. Tiba-tiba, pikiranku kosong, entah apa yang akan kujelaskan.
“Tio! saya menyuruhmu untuk menjelaskan materi, bukan untuk melamun di hadapan teman-teman yang lain. Cepat, jelaskan! Waktu kita hanya sedikit.” Pak Jari, Dosen mata kuliah Filsafat Umum, menggertakku. Aku pun tersadar dari lamunan pertanyaanku tadi. Pak Jari memang dikenal sebagai Dosen killer di kampus ini.
“eeeh, a a anu pak. Maaf, saya masih belum mengusai materi ini. Saya belum belajar.” Jawabku gagap, dengan hati yang berdetak kencang.
“Lalu mengapa kamu mengacungkan jari? Sok berani dan tahu saja.” Pak Jari berbicara dengan tegas. Nampaknya beliau marah.
Suara pak jari yang nyaring merenggut perhatian teman-temanku. Sepertinya mereka diam-diam sedang tertawa sinis di balik telapak tangan yang menutupi mulut mereka. Muka ku memerah. Sungguh, sungguh malu diri ini. Kejadian yang tak kan pernah kulupakan.
Setelah mata kuliah Pak Jari selesai. Aku pun mendatangi salah satu dari temanku. Bisa dibilang, ia adalah teman baikku selama di Yogyakarta. Putra, namanya.
“eh Putra, kau tahu mengapa teman-teman tadi acuh tak acuh ketika ku maju hendak menjelaskan materi Pak Jari itu?” kubertanya dengan suara yang lirih.
“Mengertilah, kau bukanlah Malaikat yang selalu bersujud kepada-Nya, dan kau bukanlah Syaitan yang selalu membangkang dari-Nya. Kau adalah manusia. Mengertilah manusia, Tio.” Putra hanya menjawab dengan tiga kalimat tersebut—jawaban yang kurang lebih sama dengan celotehan temanku di selasar asrama kemarin sore. Setelah itu, ia pergi meninggalkanku sebelum kumengerti apa yang ia katakan.
***
“Hey Tio, kau free enggak nanti malam? Ikut aku yuk.” Putra memanggilku ketika kuhendak mengayuh sepeda ontel, selepas kuliah berakhir.
“Iya, aku free kok nanti malam. Emang mau kemana?”
“ke Masjid Abdullah. Ada acara pengajian di sana. Mau kan kau ikut? Kau kan ahli ibadah, hihi.”
“Ah, ada-ada aja kau ini. Iya, insyaallah, Putra.”
Kemalamannya, kukenakan sarung dan kopyah hitam untuk menghadiri pengajian tersebut. Tepat pukul delapan kami berangkat ke masjid Abdulllah. Sungguh tak kuduga sebelumnya, ratusan orang memenuhi masjid Abdullah ini. Pengajian sudah dimulai. Aku dan Putra datang sedikit terlambat. Kami duduk di bagian belakang, bukan di dalam masjid, tapi di belakangnya yang beralaskan tikar. Kami hanya bisa mendengar ceramah dari corong suara. Aku membatin, siapa sih yang berceramah?.
Tak lama setelah ku duduk, dan mencari posisi ternyaman untuk menyimak pengajian, aku pun tercengang dengan kalimat pertama yang kudengar dari sang penceramah.
“Tetaplah jadi manusia, mengertilah manusia, manusiakanlah manusia.”
Apa maksud dari semua ini? Apakah semua ini hanya kebetulan saja? Manusia?, hatiku menggerutu. Semua kejadian aneh yang berembel-embel manusia kini membuatku sibuk berfikir. Celotehannya, nasihatnya, semua tentang manusia. Dan kini, tak tau siapa yang berceramah, ia juga berbicara tentang manusia.
Selama pengajian berlangsung, fikiranku dipenuhi dengan rasa kebingungan. Memikirkan hal yang sampai saat ini masih belum kumengerti. Tak terasa, pengajian telah usai. Satu persatu, orang meninggalkan masjid. Hanya beberapa orang saja yang masih di dalam, berbincang-bincang. Hey! Tunggu dulu, siapa itu? Sepertinya kumengenali orang ini. Apakah benar itu Gus Mus? Sosok figur karismatik, terkenal dengan ceramahnya yang menyejukkan hati. Untuk memastikannya, akhirnya kubertanya kepada Putra. Dan tepat sekali dugaanku, Beliau adalah Gus Mus.
Kepastian itu membuatku semakin pening. Bertanya-tanya, apa maksudnya? Gus Mus pun juga berkata seperti itu. Perasaan keingintahuan ini semakin menggebu-gebu. Kuputuskan untuk menelpon seseorang yang ia sangat berjasa dalam kehidupanku. Bapak. Semoga beliau bisa menyelesaikan semua keresahan hati ini.
Keesokan harinya, selapas shalat shubuh aku menelpon bapak. Dengan harapan yang sama, ku dapat mengerti semua ini. Bapak menjawab salamku dengan gaya bicaranya yang membuatku sungkan. Terlebih dahulu, kuberbasa-basi dengan menanyakan kabar keluarga di kampung. Lalu, setelah kumereasa cukup untuk berbasa-basi, kuberanikan diri untuk menyampaikan keluh kesah ku selama ini. Berawal dari kejadian aneh dan celotehan itu sampai kepada perkataan Gus Mus semalam.
Semuanya telah kuceritakan, kuberhenti tuk bernafas. Bapak masih terdiam. Hatiku berdebar-debar. Menunggu apa jawaban ataupun nasihat dari Bapak. Akhirnya, Bapak pun mulai berbicara.
“It magodang mangolanga, Tio. Pikir kon jolo amang. Ho angkon bisa manusia!”
Aku pun tertegun. Suara Bapak yang teduh itu menembus ulu hati. Untuk kesekian kalinya, aku mendapatkan hal yang sama. Oh Allah, harus kepada siapa lagi ku meminta penjelasan tentang hal itu. Apakah Engkau bisa memberitahuku apa jawabannya. Kutertunduk dan terdiam.
“Aku Manusia?”
___ iis usrotun {Kiim Sii Kku}
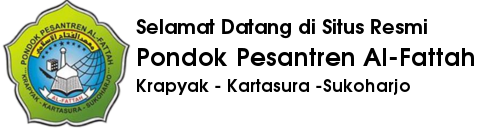






Add Comment